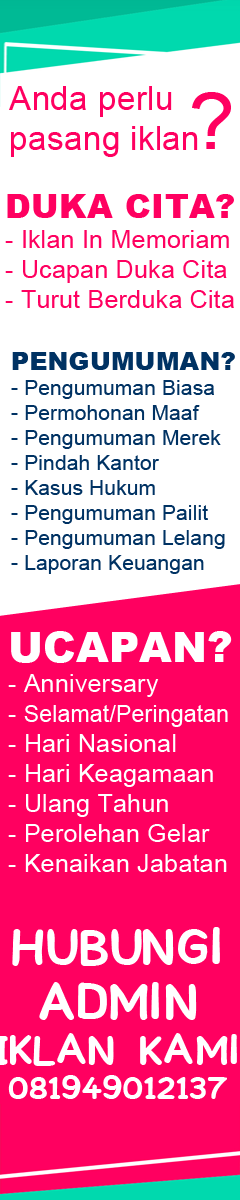Penulis: Denny JA
*(Review Pidato Hatta Rajasa Ketika Menerima
Doktor Kehormatan dari ITB)
“Negara yang berhasil dan menang adalah negara yang membangun kebijakan unggul. Kebijakan publik menentukan keberhasilan sebuah negara, apapun ideologi dan politiknya.”
Pernyataan itu dikatakan Hatta Rajasa di podium. Ia tak lagi sebagai politisi yang memimpin partai. Ia juga tak lagi sebagai Menko Ekonomi. Saat ini Hatta lebih bersosok akademisi yang banyak membaca, dan sudah dilezatkan oleh pengalaman praktis.
Saya mendengar pernyataan itu dan merenungkannya dalam- dalam. Dari Jakarta, saya naik kereta ke Bandung, semata menghadiri undangan Hatta Rajasa.
Ruangan yang banyak orang ini senyap, mendengar pidato Hatta Rajasa. Di samping guru besar ITB, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga hadir. Juga hadir banyak kolega Hatta di pemerintahan dan tokoh masyarakat.
Mengapa kebijakan publik penting? Ujar Hatta, kebijakan publik yang gagal membawa negara dalam krisis.
Hatta mengurai beberapa contoh kebijakan publik yang gagal. Bahkan negara super power sebesar Amerika Serikat dapat dilanda krisis jika ia berjudi dengan kebijakan publik resiko tinggi.
Itu terjadi di tahun 2008. Sebuah film secara apik menggambarkan drama krisis properti di Amerika Serikat: Too Big To Fail. Film doku drama ini diangkat dari buku Andrew Ross Sorkin. Siapa menduga? Lembaga keuangan sebesar Lehman Brothers yang sudah berusia 158 tahun, tanggal 15 September 2008, menyatakan diri bangkrut.
Sebanyak 84 bank tutup. Industri keuangan dan bursa rontok. Ekonomi Amerika dianggap sudah Too Big To Fail. Segala daya diupayakan. Termasuk intervensi besar besaran pemerintah meminjamkan uang untuk membuat normal situasi.
Kisah bermula dari kebijakan publik yang berniat baik. Bisnis properti termasuk bisnis yang awalnya sangat aman. Namun selama ini pinjaman bank untuk properti itu tetap dijaga dengan prinsip kehati-hatiaan.
Lalu datang kehendak Pemerintahan Clinton membuat kebijakan yang lebih populis. Diberikan kemudahan meminjam uang di bank untuk membeli properti kepada rakyat banyak. Termasuk yang diberikan kemudahan adalah segmen masyarakat yang disebut Ninja (No money, No Jobs, No Assets).
Pinjaman properti itu dikembangkan menjadi obligasi yang dijual di pasar saham oleh berbagai bisnis. Wall Street melakukan manuver membuat harga melambung berlipat.
Tiba masa yang seharusnya bisa diduga. Kelompok Ninja banyak yang tak mampu membayar pinjaman. Akibat rumah mereka disita. Semakin banyak rumah disita. Harga rumah menjadi anjlok. Seketika bangunan buble price property itu ikut anjlok.
Tak hanya ekonomi Amerika Serikat dilanda krisis. Karena obligasi properti itu juga dijual di saham internasional, negara lain ikut terseret.
Kebijakan publik dengan niat baik, yang sangat populis, berujung pada krisis negara super power.
Indonesia pernah juga mengalami kebijakan publik yang buruk. Padahal tahun 1995, lima puluh tahun Indonesia merdeka, baru saja diperingati sebagai tahun emas. Indonesia naik kelas dari negara yang awalnya miskin, dengan pendapat perkapita 100 USD, menjadi negara menengah dengan pendapatan per kapita 1000 USD.
Tapi tiga tahun kemudian, tahun 1998, krisis ekonomi terjadi begitu kerasnya. Tak hanya guncangan ekonomi. Ia menjalar pula menjadi guncangan politik. Inilah krisis yang akhirnya menjatuhkan sebuah rezim.
Penyebab krisis itu dapat dicari akarnya pada kebijakan publik yang bermasalah. Di samping tidak bekerjanya asumsi trickle down effek, pemerataan ekonomi yang tak terjadi, oligarki politik sudah pula merusak ekonomi. Pinjaman uang kepada pihak ketiga yang tak memenuhi syarat. Korupsi dan nepotisme meluas.
Dengan fasih Hatta Rajasa memaparkan sisi buruk dan sisi baik kebijakan publik. Ia uraikan sebab musabab. Begitu banyak buku dan hasil riset yang ia kutip. Diselipkannya pula pengalaman ketika ia bersama pemerintahan SBY mencoba mengatasi krisis.
What next? Apa yang tersisa di depan? Lima tahun Indonesia merdeka (1995) ditandai dengan menaiknya kelas Indonesia, dari negara miskin menjadi negara menengah. Bagaimana dengan 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 2045?
Hatta mengutip SBY. Hatta mengutip Jokowi. Hatta juga mengutip forecasting dari PricewaterHouse Copper. Baik SBY dan Jokowi menyatakan di tahun 2045, 100 tahun setelah merdeka, Indonesia potensial berkembang menjadi negara nomor lima di dunia, dari sisi kekuatan ekonomi (GDP PPP).
Bahkan PricewaterHouse lebih maju lagi. Di tahun 2050, Indonesia diprediksi menjadi kekuatan ekonomi (GDP PPP) nomor 4 di dunia, setelah Cina, Amerika Serikat dan India.
Ujar Hatta, ini bisa dicapai jika Indonesia mengembangkan kebijakan publik yang unggul. Lima agenda yang Hatta tekankan bagi kebijakan publik yang unggul.
Yang utama: penguatan sumber saya manusia, dan penguasan ilmu pengetahuan serta teknologi. Justru sumber daya manusia yang kini menjadi titik kritis Indonesia. World Economic Forum di tahun 2019 bahkan menurunkan peringkat competitiveness Indonesia dari rangking 45 ke urutan 50. Penyebab umum turun peringkat ini karena problem pada sumber daya manusia.
Di samping itu, perlu pula membangun pusat pusat ekonomi baru. Pentingnya penguatan connectivity dan infrastruktur, yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Juga mengubah ekonomi dengan komoditas yang lebih diolah (transformasi ekonomi ekstraktif menuju Value Added Economy). Dan jangan lupa menumbuhkan sebanyak mungkin entrpreneur.
-000-
Mendengar uraian Hatta, yang menekankan maha pentingnya kebijakan publik, dan kali ini Hatta mengkhususkan pada kebijakan publik bidang ekonomi, saya teringat Perdana Menteri Inggris: Tony Blair.
Ujar Hatta, Kebijakan publik menentukan keberhasilan sebuah negara, apapun ideologi dan politiknya. Ujar Tony Blair: “Saya ingin mengakhiri mengambil kebijakan yang berwarna ideologi. Kebijakan publik di bawah pemerintahan saya haruslah yang problem solving. Ia harus evidence based policy. Ia harus kebijakan yang berdasarkan pada bukti, pada data, pada riset.”
Tambah Blair: “Saya meyakini, kebijakan publik akan lebih melayani kepentingan masyarakat jika ia bersanda pada prosedur ilmiah, bukan giringan ideologi.”
Bukan hanya Hatta Rajasa dan Tony Blair, Deng Xioping juga terkenal pada pernyataannya. Tak penting warna kucing itu merah atau putih. Yang penting ia bisa menangkap tikus.
Kita memasuki era baru pemerintahan yang teknokratis. Yang dituntut dari pemerintahan adalah get things done, efektivitas, kemampuan memecahkan masalah.
Tapi bukankah manusia itu animal symbolicum? Manusia juga perlu simbol, perlu makna, penuh dengan perjuangan nilai? Bagaimana dengan nilai keadilan, dengan politik identitas, dengan agama, dengan ideologi? Kemana semua nilai itu jika kebijakan publik semakin teknokratis dan problem solving belaka?
Aneka nilai itu tentu saja terus hidup dan diapresiasi. Prinsip hak asasi manusia universal sudah melegalkannya dan membuatnya suci. Kebijakan publik masa kini tentu saja harus melindungi aneka nilai itu.
Hatta Rajasa juga menyetujui pentingnya aneka nilai itu. Hatta mengutip Tim Cook, CEO Apple Inc:
“I’m not worried about artificial intelligence giving computers the ability to think like humans. I’m more concerned about people
thinking like computers, without values or compassion, without concern for consequence”.
Namun memang tak terhindari pula, ilmu pengetahuan, teknologi dan Big Data, semakin membentuk kebijakan publik. Pemerintah semakin didesak untuk semakin efektif, semakin problem solving.
Ini era debat publik ketika data di awan data. Hasil riset dilawan hasil riset. Prinsip ilmu pengetahuan semakin bertahta. Sampai di titik ini sebenarnya semuanya biasa saja.
Namun ilmu pengetahuan kini melompat ke zaman baru. Kombinasi robot teknologi tinggi, articifial inteligence, internet of things banyak sekali menghilangkan profesi lama. Robot dengan artificial inteligence tak hanya mengganti tenaga kerja manusia yang fisik, tapi juga kerja otak.
Yuval Noah Harari menyatakan. Kita akan memasuki era ketika semakin banyak tenaga manusia tak lagi terpakai. Akan lahir kelas manusia tak bisa didayagunakan. Mereka sudah digantikan robot dan artificial inteligence yang dapat bekerja lebih cepat, lebih kuat, lebih baik, lebih akurat. Jumlah mereka semakin lama akan semakin banyak.
Di titik ini, kebijakan publik justru mendapatkan problem baru. Dan era itu sudah di depan mata.
25 November 2019